Jakarta -
Tak ada yang lebih tabah dari warga "enam dua". Hujan bulan Juni saja mungkin kalah. Hari-hari ini ketabahan manusia Indonesia yang sudah lama dikenal di segala penjuru angin dan seantero jagad raya untuk kesekian kalinya kembali diuji, dan memang terbukti "pilih tanding". Tak ada yang lebih tabah dari kita yang berkali-kali dihajar dan digempur bertubi-tubi oleh berbagai badai ujian, cobaan, dan tantangan dalam segala bentuknya, terbukti tetap tegak-tegar berdiri, bagaikan karang di tengah hempasan ombak, bagaikan dinding-dinding tebing yang memagari pantai.
Dingin, kuat, nyaris angkuh; itulah kita saking tabahnya, bangga dan memuji diri sendiri tak henti-henti. Kita baru saja dibuat geleng-geleng kepala, lalu melongo sampai mulut nyaris kemasukan lalat ijo, kemudian terkaget-kaget sampai rasanya mau kejengkang, dan berakhir dengan tawa lebar terbahak-bahak hingga pegal rahang dan pundak kita yang terguncang-guncang hebat, gara-gara pernyataan seorang ibu yang alim dan santun anggota sebuah lembaga pemerintahan yang mengatakan bahwa seorang perempuan bisa hamil kalau berenang campur dengan laki-laki dalam satu kolam.
Apa yang kita herankan sebenarnya? Apa yang membuat kita nyaris tidak percaya bahwa di zaman melimpahnya informasi saat ini, ada seorang berpendidikan tinggi, punya jabatan publik, terhormat, intelek, bisa mengeluarkan pernyataan yang sekonyol dan seabsurd itu? Tidak, bukan kekonyolan dan keabsurdan itu benar yang menusuk kalbu dan mengusik nurani kita. Pada zaman Mahabharata dulu, Dewi Kunti hamil gara-gara berjemur di bawah matahari, lalu lahirlah Karna sang perkasa, kakak para Pandawa sang pahlawan kita.
Jadi, yang membuat kita ribut, heboh, dan berolok-olok sampai nyaris marah-marah, sampai tak bisa lagi membedakan apakah kita sebenarnya sedang menangis atau tertawa, sebenarnya tak lain karena ketabahan kita menghadapi kenyataan itu. Kenyataan bahwa pernyataan yang paling konyol dan tak terbayangkan masih harus kita dengar, baca, simak, dan komentari ramai-ramai di abad yang mengobral istilah-istilah keren seperti "matinya kepakaran", "matinya demokrasi", "pasca kebenaran", "Big Data", "kecerdasan buatan", "Internet of Things", "Revolusi Industri 4.0", "Society 5.0", dan entah apa lagi....
Kita mengelus dada, menyandarkan punggung, menarik napas dalam-dalam, sambil berbisik pada diri sendiri, "Sabar, sabar...." Namun, sebelum bisikan lirih itu tertelan kembali, kita sudah dihadapkan pada pernyataan-pernyataan lain, yang datang dan pergi, yang tak kalah konyolnya, yang kembali menguji ketabahan kita. Seorang tokoh ormas dengan penuh semangat, berapi-api, dan berbusa-busa mengatakan bahwa banjir di Jakarta akibat hujan deras akhir-akhir ini hanya terjadi pada hari libur, semua itu berkat doa sang gubernur.
Bagaimana mengaitkan bencana alam dengan kesalehan seorang pemimpin? Tiba-tiba kita ingin mencakari sofa tempat kita duduk sampai koyak-moyak dan busanya berhamburan. Sejak itu, kita semakin yakin bahwa ketabahan kita memang tak akan terkalahkan oleh apapun lagi. Maka, ketika Wakil Presiden mengatakan bahwa bangsa kita sampai sejauh ini "masih aman" dari terpaan virus corona karena kita rajin membaca doa qunut saat salat subuh, jangankan untuk berdebat, kita bahkan sudah tidak punya sisa energi untuk menggumamkan komentar dalam satu kata sekalipun.
Tentu saja, sebagai insan-insan dan bangsa yang religius, kita sangat percaya dan tidak bakal berbantah-bantah lagi mengenai penting dan ampuhnya doa. Tapi, kita juga tahu, ada saat dan forum yang tepat ketika kita perlu bicara dan menegaskan kembali tentang hal itu. Pada saat seperti ini, ketika dihadapkan pada bencana dan musibah, entah itu banjir maupun wabah penyakit yang mematikan, yang pertama kali diperlukan oleh masyarakat adalah informasi yang jelas dari pemerintah bahwa telah dilakukan usaha-usaha yang sistematis, rasional, dan terukur.
Bukankah agama juga mengajarkan, usaha dulu baru doa? Dalam kasus wabah virus corona misalnya, Indonesia yang masih "aman-aman saja" di tengah negara-negara lain yang mulai "panik" dan melakukan langkah-langkah nyata --dari membatalkan salat Jumat sampai menutup kunjungan umroh-- kita perlu penjelasan yang meyakinkan, kenapa di negara kita masih "nol kasus". Sesuatu yang mestinya membuat kita tenang, patut bersyukur, dan kalau perlu berbangga (tanpa harus jumawa dan terlena), namun karena ketiadaan informasi yang jelas dari otoritas, yang ada justru sikap skeptis, was-was, dan penuh tanda tanya dalam ketidakjelasan.
Jika setiap pernyataan yang keluar dari seorang menteri hingga wakil presiden tidak membuat segala ketidakpastian itu berkurang, melainkan justru semakin menambah keraguan, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ketabahan. Barangkali kita memang ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang santai, pasrah, menghibur diri, bercanda, melucu, ngocol, dan entah apa lagi....
Dulu, pada zaman Orde Baru, juga ada seorang menteri yang akan terus dikenang karena pernyataannya yang menimbulkan kontroversi. Menurut sang menteri yang kala itu masih muda tersebut, maraknya lapangan golf (pada masa itu, yang kadang sampai harus menggusur permukiman warga), adalah indikator dari kemakmuran masyarakat. Tentu saja dia benar; maksudnya, indikator bagi yang makmur itu sendiri, sedangkan yang tergusur silakan gigit jari.
Jadi memang sudah dari dulu kita terbiasa mendapatkan pernyataan-pernyataan yang kacau, mengusik nalar, menghina akal sehat, bahkan menyakitkan hati, dari tokoh-tokoh, pejabat, dan para pemimpin yang mestinya memiliki pertanggungjawaban publik. Semua itu bisa jadi berakar pada budaya dan pendidikan kita yang tidak membiasakan dan mengajari kita untuk mengasah kemampuan mengungkapkan pernyataan dan ekspresi perasaan dengan benar.
Saya ingat, dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas tiga SMP dulu, murid-murid diminta Pak Guru untuk membuat kalimat yang benar dan menarik, dan itu terasa sebagai sebuah siksaan yang luar biasa, karena alangkah susahnya, karena --ternyata-- kita tidak mampu.
Pergilah ke acara pemakaman di kampung-kampung, dan kau bisa menyaksikan, barangkali hanya manusia Indonesia, warga "enam dua" ini, yang bisa bercanda dan tertawa di tengah upacara yang mestinya khusyuk, khidmat, dan penuh suasana duka cita.
Kita terbiasa salah menempatkan ekspresi dan sikap dalam banyak hal dan keadaan. Kita tidak terbiasa memuji, menyanjung, memberikan pernyataan yang mengapresiasi; kita lebih piawai mengolok, menyindir, atau dalam budaya Jawa secara khusus ada istilah "pasemon", "nyemoni", sebuah "seni" untuk mengungkapkan perasaan negatif tanpa terkesan menyakitkan, tapi efek mentalnya justru luar biasa menohok tajam, menghunjam perasaan yang paling dalam, membekas, dan susah dilupakan. (Bayangkan, untuk sesuatu yang sebenarnya bertujuan untuk menyakiti pun, kita punya cara yang samar agar tidak mencolok, tapi hasilnya sama saja!)
Kita selalu ingin melucu, melawak, tapi selalu salah tempat, tidak pas dengan suasana, dan gagal. Kita berlagak sok santai di saat situasi sebenarnya menghendaki keseriusan, dan sebaliknya tegang, kenceng, "ngegas" di saat yang mestinya perlu bersikap santai, wajar, dan biasa-biasa saja. Pendek kata, kita tidak peka; tidak pandai bersimpati, dan tidak punya empati. Berbagai "kearifan lokal" yang mulia seperti welas asih, tepa slira, dan empan papan hanya menjadi jargon pucat, lebih sekadar untuk mengklaim keagungan primordial, membanggakan kelompok, dan bukannya menjadi praktik keutamaan yang melekat dan "spontan" dalam pergaulan kehidupan.
Kita bahkan sulit sekali mengucapkan "terima kasih". Berilah bangku pada orang lain di transportasi umum, dan biasanya orang tersebut akan segera menerimanya bahkan tanpa menoleh ke arah kita untuk sekadar beradu pandang sebagai isyarat ucapan terima kasih, atau minimal memberikan senyuman paling tipis sekalipun. Budaya kita lebih mengajarkan untuk selalu menyerobot, mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang banyak, dan tak peduli. Sebaliknya, ketika kepentingan sendiri terusik sedikit saja, begitu mudahnya kita tersinggung, marah, nyolot, dan entah apa lagi....Yang punya utang lebih galak ketika ditagih oleh yang punya piutang!
Di jalanan, dua orang pengendara yang sama-sama melanggar aturan, dan karena satu dan lain hal, karena yang satu merasa terusik atau entah bagaimana, bisa berantem sendiri di tengah jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya yang lebih banyak, yang menggunakan jalan sesuai peraturan. Yang tertib dan mentaati peraturan bisa menjadi minoritas dan malah menjadi "kalah gertak" oleh yang melanggar peraturan, karena jumlah mereka bisa jadi lebih banyak, dan melanggar itu sudah menjadi kebiasaan, dianggap wajar, sehingga seolah-olah justru merekalah yang benar.
Hal-hal kecil dan terkesan --atau kita anggap-- remeh tersebut merembet pada tatanan yang lebih besar dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti hukum dan berbagai peraturan di level kekuasaan dan pengambil kebijakan. Atau, jangan-jangan justru sebaliknya, berbagai kekacauan di tingkat bawah itu cerminan dan akibat dari hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan negara yang semestinya mengayomi, memberi rasa aman, menjamin keadilan dan ujungnya membuat kehidupan masyarakat tertata, nyaman, dan tenteram, namun kenyataannya justru lebih sering memberikan ketidakpastian dan perasaan terancam? Wallahualam.
Mumu Aloha wartawan, penulis, editor
(mmu/mmu)
Let's block ads! (Why?)
"dari" - Google Berita
March 01, 2020 at 12:06PM
https://ift.tt/2PBaypY
Tak Ada yang Lebih Tabah dari Warga "Enam Dua" - detikNews
"dari" - Google Berita
https://ift.tt/2rCl872
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update


/data/photo/2020/02/29/5e5a90336382b.jpg)

/data/photo/2020/02/29/5e5a17d9d1ea7.jpg)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3063759/original/076940000_1582916534-UMKM_BANYUMAS_2-ridlo.jpg)
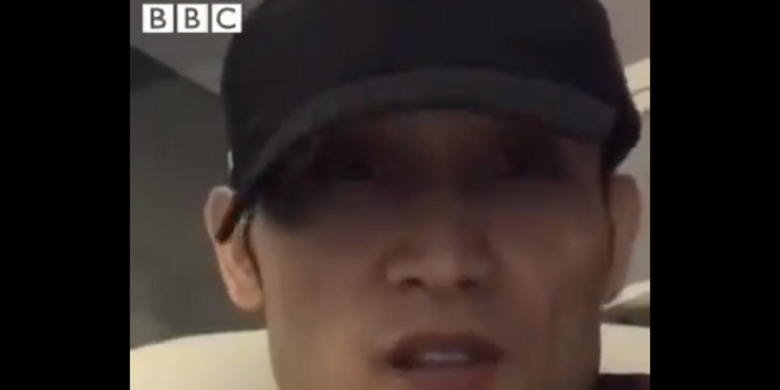



/data/photo/2020/02/29/5e5a5eae14a6b.jpg)


